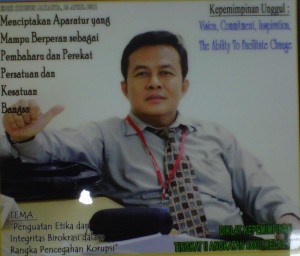Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan pembuatan undang-undang, peraturan pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif (DPR). Di berbagai negara, istilah yang digunakan antara lain delegated legislation, subordinate legislation, secondary legislation, subsidiary legislation, legislative instruments, atau statutory instruments.
Pada dasarnya kewenangan membuat undang-undang, termasuk peraturan pelaksanaannya, ada di tangan lembaga legislatif. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Namun, suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlunya pengaturan yang detil, memerlukan keahlian khusus, dan pengaturan yang harus sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Selain itu, secara praktis, mekanisme penetapan suatu keputusan yang panjang dan rumit tidak memungkinkan dibuat sendiri oleh DPR.
Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif menjadi lebih cepat prosesnya karena tidak memerlukan debat di DPR yang seringkali berlarut-larut. Waktu DPR akan tersita untuk membahas hal detil. Seringkali diperlukan pengaturan yang mendesak dan segera harus diberlakukan, misalnya pengaturan mengenai kenaikan jalan tol atau kenaikan harga BBM. DPR dengan mekanisme pengambilan keputusan yang ada tidak mungkin dapat menghasilkan peraturan seperti itu.
Seringkali kebijakan teknis perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah peraturan pelaksanaan daripada mengubah undang-undangnya. Apabila kebijakan teknis diserahkan kepada DPR, maka waktu DPR akan tersita untuk membahas hal yang bersifat teknis. Contoh peraturan yang demikian adalah peraturan mengenai perubahan organisasi pada kementerian.
Kementerian dan lembaga cenderung lebih mampu membuat pengaturan yang efektif karena merupakan area keahlian mereka. Khusus peraturan daerah, mereka lebih mengetahui kondisi masing-masing daerah setempat. Sebagai contoh peraturan mengenai tata ruang suatu wilayah.
Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan memiliki beberapa manfaat, yakni menghindari salah satu cabang kekuasaan (eksekutif atau legislatif) mendominasi kekuasaan sehingga dan tidak menciptakan prinsip checks and balances kekuasaan. Apabila peraturan pelaksanaan didominasi oleh legislatif, dalam arti peraturan pelaksanaan dibuat oleh legislatif, secara praktis dapat menghambat pelaksanaan suatu undang-undang oleh eksekutif mengingat legislatif tidak mengetahui praktik pelaksanaan secara detail dan pengaturan lokal. Sebaliknya apabila peraturan pelaksanaan dibuat secara penuh oleh eksekutif, maka akan berpotensi kekuasaan legislatif akan diambil alih oleh eksekutif. Selain itu, mencegah eksekutif menyelenggarakan pemerintahan secara tidak terkendali. Adanya delegasi kewenangan dari legislatif kepada eksekutif akan mencegah eksekutif melakukan improvisasi yang tidak tepat dalam menyelanggarakan pemerintahan.
Jenis Peraturan Pelaksanaan
1. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
2. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
3. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Peraturan Menteri
Keberadaaan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan merupakan perkembangan baru. Beberapa undang-undang belakangan ini mendelegasikan kewenangan legislasi secara langsung kepada menteri. Sebelumnya instrumen peraturan pelaksanaan yang digunakan untuk mengatur lebih lanjut undang-undang adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden.
5. Peraturan Kepala Lembaga (BI, BPK, DPR)
Beberapa undang-undang mendelegasikan kepada lembaga tertentu seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DPR.
Kekurangan Peraturan Pelaksanaan
Pemberian delegasi pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif mengandung risiko kurangnya publikasi dan diseminasi. Kurangnya pengawasan serta kurangnya publikasi dan diseminasi mengakibatkan ketentuan yang dibuat dalam peraturan pelaksanaan berpotensi menyimpangi, memperluas, atau mempersempit materi undang-undang. Selain itu, lembaga eksekutif juga cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya ketika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur. Hal ini banyak terjadi ketika peraturan pelaksanaan mengatur mengenai kewenangan kelembagaan. Kementerian/lembaga secara naluriah cenderung menginginkan kewenangan yang besar.
Akibat lainnya adalah pengambilan keputusan dalam membuat peraturan pelaksanaan kurang transparan dan demokratis. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan atas penggunaan wewenang pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang setidaknya oleh internal eksekutif.
Pengawasan Peraturan Pelaksanaan
Secara teori, terdapat tiga jenis pengawasan pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang yakni pengawasan oleh internal lembaga eksekutif, oleh lembaga legislatif (DPR), dan oleh pengadilan (Mahkamah Agung/MA). Pengawasan oleh internal eksekutif dilaksanakan melalui forum harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan forum finalisasi di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Sementara, pengawasan oleh lembaga legislatif dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan oleh lembaga legislatif biasanya dilakukan ketika suatu peraturan pelaksanaan menjadi kontroversial di masyarakat, seperti perpres tentang minuman beralkohol yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Anggota DPR berpendapat atas masalah ini. Namun, tidak ada instrumen khusus dan kewenangan langsung DPR untuk bisa mengevaluasi perpres tersebut, sehingga pendapat Dewan hanya sebatas menekan untuk membatalkan suatu peraturan pelaksanaan.
Pengawasan oleh Pengadilan dilakukan dengan mekanisme uji materi (judicial review). MA dapat menyatakan suatu peraturan pelaksanaan bertentangan dengan undang-undang, baik bertentangan secara substantif maupun secara formal (prosedural). Pertentangan dengan undang-undang terjadi ketika suatu peraturan pelaksanaan undang-undang menyimpangi, memperluas, atau mempersempit ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain menguji pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi MA juga dapat menguji apakah suatu peraturan pelaksanaan bertentangan dengan kepentingan umum atau mengandung ketentuan yang bertentangan dengan norma susila.